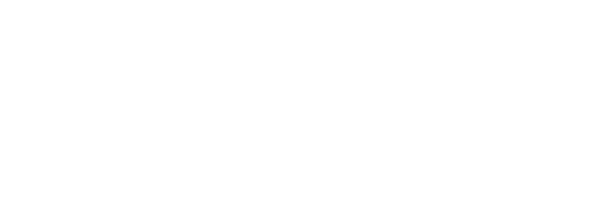Sebuah ulasan dari Syaiful Arif (intelektual dan tokoh muda Nahdlatul Ulama)
Kabar5news – Dalam khazanah sastra Indonesia yang terus berevolusi, ada kalanya sebuah tulisan hadir bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk dirasakan, direnungkan, dan menggetarkan kesadaran. “Kiri Namanya,” sebuah prosa reflektif karya Taufan Hunneman yang dimuat di Kabar5news.id pada 16 Oktober 2025, adalah salah satu permata semacam itu. Lebih dari sekadar artikel, karya ini adalah sebuah puisi esai yang menyentuh relung-relung paling dalam dari memori kolektif kita, mengajak kita menyelami secara lebih sastrawi makna yang terpenjara di balik sebuah kata yang sarat beban: kiri.
Dengan gaya bahasa yang puitis, kontemplatif, dan penuh dengan metafora yang cermat, Taufan Hunneman membawa kita pada sebuah pelayaran intelektual dan emosional. Ia tidak menggurui atau menyajikan data mentah, melainkan merajut kata-kata menjadi jaring pertanyaan filosofis yang menggugah dan membuka ruang dialog yang lapang. Dari kalimat pembukanya, kita sudah dihadapkan pada sebuah realitas yang pahit namun harus diakui: kata “kiri” telah menjadi semacam “tuduhan pamungkas,” sebuah label yang mampu membekukan dialog, menutup segala pintu nalar, dan mengakhiri pertemanan. Dalam goresan penanya, Taufan melukiskan betapa sebuah kata bisa berubah menjadi hantu yang menghantui percakapan politik bangsa.
Keindahan dan kedalaman prosa ini terutama terletak pada upaya Taufan yang gigih namun elegan untuk membebaskan kata “kiri” dari penjara stigmatisasi yang telah mengkarat selama puluhan tahun. Dengan tangan yang halus dan nalar yang jernih, ia mengelus debu prasangka yang menutupi inti berlian dari gagasan ini. Taufan dengan lihai mengingatkan kita bahwa pada hakikatnya, semangat “kiri” adalah semangat universal yang berporos pada keadilan sosial, emansipasi, dan pembelaan tanpa syarat pada kaum yang terpinggirkan (mustada’afin). Dalam titik terang pencerahan yang ia tawarkan ini, “kiri” bukanlah monster asing yang menakutkan, melainkan semangat yang justru beresonansi dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan keagamaan—sebuah teriakan hati nurani untuk melawan ketidakadilan dalam segala bentuk manifestasinya. Ia menyelaraskan konsep yang sering dianggap sekuler ini dengan jiwa religius yang dalam, menciptakan harmoni pemahaman yang menawan.
Salah satu momen paling berkesan dan brilian dalam prosa ini adalah ketika Taufan Hunneman dengan cerdik dan sederhana mempertanyakan, “Lawan dari kiri itu apa?” Pertanyaan yang tampaknya sederhana ini bagai sangkakala yang membangunkan kita dari tidur dogmatis yang panjang. Ia memecah kebekuan berpikir dengan kejernihan logika. Jika “kiri” adalah tentang membela yang lemah, maka bukankah lawannya adalah pembiaran terhadap kesewenangan? Jika “kiri” adalah tentang teriakan lantang untuk keadilan, maka bukankah lawannya adalah bisingnya suara terhadap ketidakadilan itu sendiri? Di sini, Taufan berhasil mengalihkan fokus kita dari sebuah label yang menakutkan dan sering kali kosong makna, kepada substansi nilai yang seharusnya kita perjuangkan bersama sebagai sebuah bangsa yang beradab.
Sebagai sebuah karya sastra, kekuatan “Kiri Namanya” tak lepas dari pilihan diksi, irama bahasa, dan struktur kalimat yang dibangunnya. Taufan menulis dengan nada yang intim, reflektif, dan personal, seolah-olah ia sedang berbagi hasil permenungannya yang paling jujur di sebuah ruang yang sunyi bersama pembaca. Pengulangan yang ritmis dan pertanyaan retoris yang ia selipkan secara strategis menciptakan sebuah lantunan mantra yang secara perlahan namun pasti membuka pikiran dan hati pembaca. Ia tidak memaksa atau menghakimi, tetapi membimbing dengan lembut melalui lorong-lorong pemikiran yang mungkin selama ini kita hindari.
Prosa ini juga merupakan sebuah penghormatan yang dalam terhadap kekuatan dan luka ingatan kolektif. Taufan menyentuh dengan halus dan penuh empati bagaimana trauma masa lalu, yang ditanamkan secara sistematis oleh rezim Orde Baru, telah membentuk persepsi dan bahkan ketakutan irasional kita hingga hari ini. Namun, ia menyampaikannya bukan dengan kemarahan atau dendam, melainkan dengan semangat untuk menyembuhkan, merekonstruksi, dan merekonsiliasi masa lalu dengan masa kini. Ia mengajak kita untuk berani melihat sejarah dengan kacamata yang lebih jernih, lebih kritis, dan lebih manusiawi.
Pada akhirnya, “Kiri Namanya” karya Taufan Hunneman adalah sebuah oase kebijaksanaan dalam gurun wacana publik Indonesia yang sering kali kering, panas, dan penuh dengan permusuhan. Karya ini adalah sebuah undangan yang elegan dan sophisticated untuk melakukan introspeksi mendalam, untuk memeriksa ulang kata-kata yang kita gunakan dan prasangka yang tanpa sadar kita peluk erat. Taufan berhasil mengangkat diskusi yang sering kali keras, dikotomis, dan penuh amarah ke dalam ranah sastra yang lembut, tenang, namun justru penuh daya tembus dan makna.
Sebagai sebuah karya, prosa ini bukan hanya sukses secara estetika bahasa, tetapi juga menjadi sebuah dokumen sosial yang penting bagi zamannya. Ia adalah nyala api kecil yang lembut namun tak kunjung padam, mengingatkan kita bahwa di balik segala perdebatan ideologis yang kerap mengaburkan, inti dari segala perjuangan adalah cita-cita mulia dan universal akan sebuah dunia yang lebih adil, setara, dan berprikemanusiaan. Sebuah karya yang patut dikenang, dijadikan bahan diskusi, dan disebarluaskan.
Yang membuat prosa ini semakin bernas adalah kemampuannya berbicara pada zaman tanpa terikat oleh waktu. Ditulis di era di mana polarisasi politik sering mengerdilkan nuansa, Taufan justru mengajak kita merayakan kompleksitas. Ia mengingatkan bahwa sebelum kita terjebak dalam debat kusir tentang label dan cap, ada nilai-nilai fundamental kemanusiaan yang harus kita junjung bersama. Dalam gemuruh era media sosial di mana setiap pihak merasa paling benar, suara tenang dan mendalam seperti ini bagai oase di padang gurun.
Kehadiran prosa ini di Kabar5news.id pada Oktober 2025 juga patut diapresiasi. Di tengah dominasi berita-berita politik yang sering kali sensasional dan reaktif, media ini berani memberikan ruang bagi karya reflektif yang justru mengajak pembaca untuk melambat dan merenung. Pilihan ini menunjukkan keberpihakan pada substansi di atas sensasi, pada kedalaman di atas kecepatan. Taufan, dengan latar belakangnya sebagai pemikir yang telah lama mengamati dinamika sosial-politik, membawa kredibilitas dan kedalaman yang jarang ditemui dalam tulisan-tulisan populer.
Lebih dari itu, prosa ini berhasil menjembatani kesenjangan antara wacana akademis yang kerap terlalu teknis dan wacana publik yang sering kali terlalu simplistis. Taufan tidak terjebak dalam jargon-jargon teoritis yang membingungkan, tetapi juga tidak merendahkan kecerdasan pembaca dengan penyederhanaan yang berlebihan. Ia menemukan titik keseimbangan yang sempurna, di mana kompleksitas ide disampaikan dengan kejelasan bahasa yang memukau. Inilah mungkin salah satu kontribusi terbesarnya: mendemokratisasikan wacana kritis yang selama ini seolah hanya menjadi milik kalangan tertentu.
Pada akhirnya, “Kiri Namanya” bukan sekadar tentang politik atau sejarah. Ini adalah prosa tentang keberanian untuk berpikir jernih di tengah hiruk-pikuk, tentang integritas untuk tidak mudah terprovokasi oleh stigma, dan tentang kebijaksanaan untuk melihat esensi di balik label. Dalam setiap barisnya, Taufan Hunneman tidak hanya menulis dengan pikiran, tetapi juga dengan hati – sebuah kombinasi langka yang membuat karyanya tidak hanya cerdas tetapi juga menyentuh jiwa.
Dengan demikian, prosa ini telah melampaui fungsinya sebagai sekadar tulisan. Ia telah menjadi semacam cermin bagi setiap pembacanya – mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri: nilai-nilai apa yang sebenarnya kita perjuangkan, dan sejauh mana kita berani konsisten pada nilai-nilai itu meski menghadapi tekanan dan stigmatisasi? Inilah kekuatan sastra sejati – bukan memberikan jawaban, tetapi melahirkan pertanyaan-pertanyaan bermartabat dalam diri setiap orang yang membacanya.