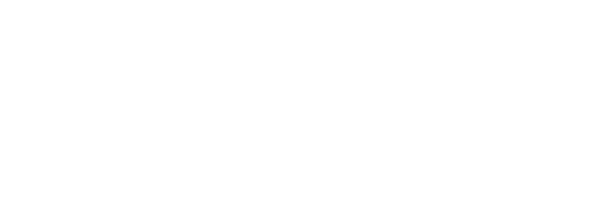Kabar5News – Jakarta, tahun 1940-an. Di tengah kepulan asap kretek dan aroma kopi tubruk di kawasan Senen, seorang pria dengan rambut acak-adakan dan mata merah yang tajam sering terlihat luntang-lantung.
Ia tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya rumah tinggal yang mapan, dan seringkali menumpang makan di rumah kawan. Namun, dari saku kemejanya yang lusuh, lahir kalimat-kalimat yang meruntuhkan tembok kaku sastra Indonesia lama.
Pria itu adalah Chairil Anwar. Seorang bohemian sejati yang membuktikan bahwa menjadi seniman bukan sekadar hobi, melainkan sebuah cara hidup yang radikal.
Sebelum Chairil muncul, sastra Indonesia didominasi oleh angkatan Pujangga Baru yang cenderung mendayu-dayu, penuh rima yang teratur, dan bahasa yang sangat santun.
Chairil datang dan mendobrak itu semua. Ia tidak peduli pada aturan. Ia membawa bahasa sehari-hari, bahasa jalanan, bahkan bahasa umpatan ke dalam baris-baris puisinya.
Ia adalah pelopor Angkatan ’45. Jika penyair sebelumnya menulis tentang indahnya gunung dan bunga dengan kata-kata manis, Chairil menulis tentang kematian, eksistensi diri, dan pemberontakan.
“Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang…”
Kalimat legendaris dari puisi berjudul Aku di atas bukan sekadar metafora. Itu adalah pernyataan posisi; Chairil memilih untuk berada di luar sistem, di luar kenyamanan, demi kejujuran artistik.
Hidup Bohemian
Istilah bohemian sering disematkan pada mereka yang hidup bebas tanpa mempedulikan norma sosial demi seni. Chairil adalah personifikasi dari istilah ini. Ia hidup berpindah-pindah, dan terkadang “meminjam” buku dari toko tanpa membayar demi memuaskan dahaganya akan ilmu.
Bagi Chairil, tubuh hanyalah wadah yang boleh rusak, asalkan karyanya abadi. Ia mengonsumsi buku-buku sastra dunia seperti karya Rilke, Slauerhoff, dan Nietzsche, lalu meramu napas dunia itu ke dalam konteks kemerdekaan Indonesia.
Kejeniusan Chairil terletak pada kemampuannya memprediksi kegelisahan manusia modern. Di saat bangsanya sedang sibuk dengan euforia fisik kemerdekaan, Chairil sudah bicara tentang kesepian individu, ketakutan akan maut, dan pencarian jati diri yang tak kunjung usai.
Ia terlalu maju untuk zamannya. Ketika orang lain masih bergelut dengan struktur kalimat yang baku, ia sudah bermain dengan tipografi dan diksi yang meledak-ledak. Ia memahami bahwa puisi bukanlah laporan berita, melainkan rekaman jiwa yang paling jujur.
Warisan yang Tak Pernah Mati
Meski raganya telah lama beristirahat di TPU Karet Bivak, Chairil Anwar tetap menjadi kompas bagi penulis muda hingga hari ini. Ia mengajarkan bahwa menjadi penulis berarti berani menjadi diri sendiri, meski harus “terbuang dari kumpulannya.”
Hidupnya singkat, ia meninggal di usia 26 tahun, namun intensitas hidupnya setara dengan mereka yang hidup berabad-abad. Puisi-puisi juga semangatnyapun tetap hidup hingga kini, sebagaimana digambarkan dalam penggalan puisi Aku;
“Aku ingin hidup seribu tahun lagi…”