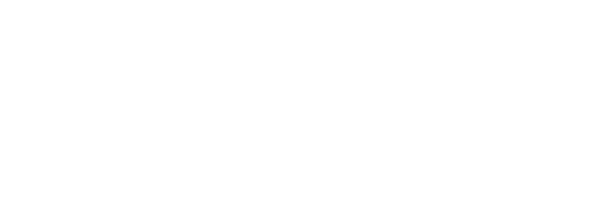Kabar5News – Gunung Anak Krakatau (GAK), yang terletak di Selat Sunda, kembali menjadi berita seiring dengan status terkini aktivitas vulkaniknya yang berada di Level II (Waspada). Meskipun status ini mengindikasikan bahwa aktivitasnya berada di atas normal dan masyarakat/wisatawan diimbau untuk tidak mendekati kawah aktif dalam radius tertentu (umumnya 2 kilometer), kondisi ini selalu mengingatkan kita pada sejarah kelam dan dahsyatnya “induk”nya, Gunung Krakatau, pada tahun 1883.
Data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menunjukkan bahwa GAK berada pada level Waspada. Aktivitas yang terekam meliputi adanya kegempaan vulkanik, baik dangkal maupun dalam, serta tremor menerus dengan amplitudo yang kecil. Asap kawah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis.
Level II ini memerlukan kewaspadaan dan larangan mendekati kawah aktif, namun berbeda dengan Level III (Siaga) atau Level IV (Awas) yang menuntut evakuasi dan radius bahaya yang lebih luas. Kondisi ini adalah pengingat bahwa GAK adalah gunung api aktif yang terus tumbuh dan membangun tubuhnya sejak ia muncul pada tahun 1927, di tengah kaldera sisa letusan maha dahsyat Krakatau.
Kilas Balik Letusan Krakatau 1883
Kontras dengan aktivitas GAK yang cenderung lokal, letusan Gunung Krakatau pada 26-27 Agustus 1883 adalah salah satu peristiwa geologi paling katastrofik yang pernah dicatat sejarah. Letusan paroksimalnya melepaskan energi yang diperkirakan setara dengan 200 megaton TNT, hampir empat kali lipat kekuatan senjata termonuklir terkuat yang pernah diledakkan.
Dampak dari ledakan tersebut sungguh luar biasa, suara ledakan letusannya terdengar hingga jarak lebih dari 3.000 mil (sekitar 4.800 km). Sekitar 20 juta ton sulfur dilepaskan ke atmosfer, menyebabkan musim dingin vulkanik yang menurunkan suhu rata-rata global selama lima tahun. Dan, lebih dari 36.000 orang tewas, sebagian besar disebabkan oleh tsunami raksasa setinggi hingga 30 meter yang melanda pesisir Banten dan Lampung.
Dampak letusan Krakatau tahun 1883 bahkan menjangkau ke belahan bumi lain dan menginspirasi salah satu karya seni paling ikonik di dunia: “The Scream” (Der Schrei der Natur) oleh pelukis Norwegia, Edvard Munch.

Lukisan yang dibuat pada tahun 1893, sepuluh tahun setelah letusan, menampilkan sosok yang diliputi kecemasan di atas jembatan dengan latar belakang langit berwarna merah darah yang menyala-nyala. Dalam catatan hariannya, Munch menulis, “Saya sedang berjalan di sebuah jalan kecil dengan dua orang teman — matahari sedang tenggelam, mendadak langit berubah menjadi merah darah. Saya merasakan jeritan yang tidak henti-hentinya melintas di alam raya.”