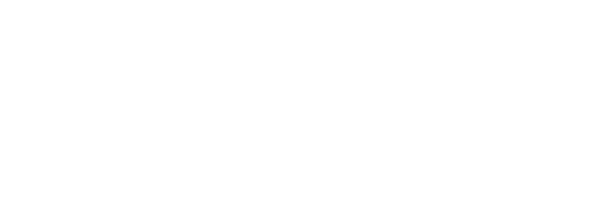Kabar5News – Proklamasi baru saja dideklarasikan.
Euforia menyebar ke seluruh pelosok kota Jakarta.
Orang-orang berhamburan keluar rumah, meneriakkan pekik kemerdekaan.
Suasana hari itu dipenuhi kebahagiaan yang bercampur haru.
Namun, di sudut kota Jakarta, tepatnya di belakang Sekolah Kedokteran STOVIA, suasana justru mencekam.
Fritz baru saja bertengkar hebat dengan istrinya, Elizabeth.
Sesekali, rumah mereka yang terletak di belakang STOVIA dilempari batu.
Coretan-coretan di dinding begitu mengerikan:
“Antek kolonialis!”
“Bakar!”
“Bunuh!”
“Enyahkan mereka yang mengatasnamakan pemuda rakyat!”
Fritz dan Elizabeth termasuk golongan Eropa berdasarkan klasifikasi kewarganegaraan.
Meski tergolong Eropa, Fritz bukan orang Belanda.
Ia adalah warga Jerman yang datang sebagai pengusaha elektronik sekaligus kontraktor pembangunan instalasi listrik.
Fritz muda pernah berkelana dari Austria, Jerman, Surabaya, hingga Batavia.
Pertemuannya dengan Elizabeth adalah misteri cinta.
Elizabeth dikenal sebagai pribadi tertutup. Ayahnya bermarga Snijders, seorang yang sejak muda menolak gaya hidup pegawai VOC yang lazim melakukan pergundikan.
Snijders muda justru menikahi seorang gadis pegawai rendahan di perkebunan bernama Sun, yang berdarah campuran Kediri–Minahasa.
Elizabeth adalah perempuan terpelajar. Ia menempuh pendidikan keperawatan di Utrecht.
Sebagian besar gadis Minahasa di tanah kolonial bercita-cita menjadi perawat, terlebih di Tomohon yang memiliki banyak rumah sakit, sekolah, dan organisasi yang lahir dari semangat zending.
Fritz mempekerjakan banyak karyawan, sebagian besar berasal dari Aceh.
Ia menyukai semangat kerja orang Aceh yang dikenal disiplin dan taat beragama—suatu keuntungan bagi Fritz dalam menghadapi pegawai yang tidak membuat onar.
Kemerdekaan bagi keluarga mereka justru menjadi awal petaka.
Dua anak mereka yang sudah besar ditahan di kamp konsentrasi Jepang di daerah Cileungsi, sementara anak sulung bergabung dengan Tentara Kerajaan Belanda.
Yang tersisa di rumah adalah Ron (11 tahun), Ruben (8 tahun), Noah (7 tahun), Debora (5 tahun), dan satu bayi yang masih dalam kandungan, kelak diberi nama Deasy.
—
Hari ini, semua anak mendengarkan percakapan kedua orang tuanya.
Elizabeth bersikeras ingin meninggalkan Indonesia. Ia bahkan telah mendaftarkan diri untuk ikut kapal yang akan berlayar menuju Belanda.
Sementara itu, Fritz mendapat kabar dari beberapa sumber bahwa tanah kelahirannya telah hancur berantakan.
Negaranya terpecah menjadi dua wilayah: bagian barat yang kelak dikenal sebagai Jerman Barat dikuasai oleh Sekutu, dan bagian timur yang dikuasai oleh Tentara Merah, kelak disebut Jerman Timur.
Namun, bukan itu alasan utama Fritz menolak pergi. Ia sudah terlanjur jatuh cinta pada negeri ini.
Ia enggan meninggalkan segala usaha, kerja keras, dan fondasi ekonomi yang telah ia bangun selama bertahun-tahun.
Keluarga Fritz tergolong keluarga berada. Mereka memiliki rumah besar dan sebuah vila di kawasan Bogor, tempat mereka biasa berkumpul dan menikmati masa-masa keemasan pada dekade 1930–1942.
Sebenarnya, Fritz lolos dari penangkapan pada masa pendudukan Jepang karena ia termasuk golongan Eropa asal Jerman.
Namun, nasib buruk menimpa dua anaknya yang tertangkap di Bogor dan harus masuk ke kamp konsentrasi.
Ketika kamp itu ditinggalkan begitu saja, mereka terpaksa berjalan berhari-hari untuk kembali ke kota Bogor.
—
*November 1945*
Adalah masa kelabu.
Elizabeth pergi meninggalkan Indonesia, meninggalkan anak-anak lelakinya.
Hanya Debora yang masih bersamanya, serta Deasy yang masih dalam kandungan.
Elizabeth tidak membawa banyak uang, hanya sedikit untuk bekal perjalanan.
Ia terdaftar sebagai tenaga perawat, dan berkat keterampilan itulah, sebagai seorang Indo, ia kelak tidak mengalami persekusi di negeri Belanda.
Fritz menyuruh Tikno, orang kepercayaannya, untuk mengantar Elizabeth ke pelabuhan.
Fritz melepaskan istrinya yang telah banyak memberi makna dalam perjuangan merintis usaha dan membangun kehidupan.
Tiga hari mereka tenggelam dalam kesunyian.
Elizabeth akhirnya pergi, dan sejak saat itu ia hancur—meninggalkan kenangan, keindahan, serta masa-masa bersama yang tak tergantikan.
Fritz pun berubah; ia lebih banyak diam dan menyendiri.
Rumah-rumah diserbu.
Dibakar.
Beberapa orang dari golongan Eropa mengalami pelecehan, pemukulan, dan kebencian yang begitu mendalam.
Kehancuran moral merajalela.
Rumah Fritz dijaga oleh orang-orang dari Pejambon, yang berasal dari Menado dan Maluku.
Para pegawai Fritz juga turut menjaga, sehingga rumah itu luput dari amuk massa yang dilakukan oleh para pemuda rakyat.
Rumah keluarga Simon hancur.
Rumah keluarga Beekman terbakar.
Akhirnya, mereka semua menyatu dan berlindung di rumah keluarga Fritz.
Mereka, golongan Eropa, hidup dalam ketakutan.
Pemukulan, pelecehan, hingga puncaknya: nasionalisasi aset dan unit-unit usaha.
Fritz membayangkan betapa perubahan itu begitu drastis.
Para pemimpin negeri yang baru lahir menyamaratakan segalanya.
Fritz teringat pada tokoh-tokoh dari golongan Eropa seperti Douwes Dekker, Setiabudi, dan para anggota Indische Partij.
Mereka, meski secara klasifikasi kewarganegaraan termasuk golongan Eropa, sangat mencintai negeri ini.
Beberapa tahun kemudian, dua anak Fritz—Donald dan John—terlibat dalam gerakan Permesta, lalu pergi ke Belanda pada tahun 1959.
Sementara anak sulungnya bergabung sebagai kru Armada Laut Kerajaan Belanda, Karel Doorman, yang kelak turut meluluhlantakkan armada Yos Sudarso dalam perang Papua tahun 1962.
—
Fritz menyaksikan satu per satu anaknya kecewa terhadap negeri yang begitu ia cintai.
Mereka memilih pergi ke Belanda dan Amerika Serikat.
Hanya satu anak yang tetap setia menemaninya: Ron.
Fritz berbisik lirih,
“Tidakkah kau seharusnya pergi juga? Adik-adikmu, Ruben dan Noah, sudah meninggalkan negeri ini.”
Ron menjawab pelan, “Aku baru saja mendaftar menjadi anggota TNI.”
Mata Fritz berkaca-kaca.
Air matanya menetes.
“Kau… masih mencintai negeri ini?
Setelah semua pergolakan,
aksi massa diam,
pelecehan,
pemukulan,
bahkan seluruh usahaku dinasionalisasi…
Kau masih memilih bertahan?
Kelak kau akan menjadi seorang diri.
Sebab seluruh keluargamu—tante, om, kakak, bahkan adikmu—telah pergi.”
Ron menjawab dengan tenang,
“Semua peristiwa itu bukan alasan bagiku untuk pergi.
Aku punya alasan yang lebih kuat.
Kelak, tanah ini akan memberiku hidup sebagai tanah perjanjianku.”
Ron kemudian masuk pendidikan militer di Kalijati, di markas Parako (Para Komando PGT—Pasukan Gerak Cepat).
Ia melepaskan kewarganegaraan Eropa dan memilih menjadi warga negara Indonesia.
Diceritakan, Ron menjadi bagian dari satuan pasukan elite penerjun Para Komando.
Bertahun-tahun kemudian, pada hari pemakamannya di awal 2000-an, banyak orang mengenang perjalanan hidupnya.
Ron dikenal sebagai perwira pasukan elite penerjun Para Komando.
Pangkatnya ia raih dari garis operasi: DI/TII, Permesta—di mana ia berhadapan langsung dengan kakak dan sanak saudaranya—pemberantasan PKI, serta operasi di Kalimantan untuk menumpas sisa-sisa gerakan pemuda rakyat yang dulu memotori aksi massa diam dan pembantaian kaum Indo pada era 1945.
Ia juga terlibat dalam Operasi Dwikora dan turut menyiapkan para serdadu muda untuk dikirim ke Timor-Timor.
Kelak, putrinya menikah dengan seorang prajurit yang pernah ia latih sepulang dari Timor-Timor tahun 1982.
Anak dan cucunya kemudian masuk menjadi anggota TNI dan kepolisian.
Nasionalisme—cinta tanah air—menjadi DNA keluarga Ron.
*Tamat*