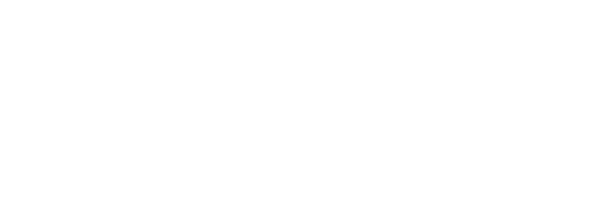Kabar5News – Perang Aceh (1873–1914) tercatat sebagai salah satu palagan paling berdarah dan melelahkan dalam sejarah kolonialisme Belanda di Nusantara. Selama puluhan tahun, Kerajaan Belanda dibuat frustrasi oleh taktik gerilya, fanatisme agama, dan ketangguhan pejuang Aceh.
Pada akhir abad ke-19, militer Belanda menyadari bahwa pasukan infanteri biasa yang terbiasa dengan pola perang Eropa tidak akan pernah menang di hutan Aceh. Atas saran dari Christiaan Snouck Hurgronje, seorang orientalis yang mempelajari struktur sosial Aceh, Belanda membentuk Korps Marsose.
Korps Marsose (bahasa Belanda: Korps Marechaussee te Voet) adalah satuan militer elite yang dibentuk oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada tahun 1890. Pembentukannya merupakan jawaban atas kegagalan tentara reguler Belanda (KNIL) yang selalu kewalahan menghadapi taktik gerilya rakyat Aceh yang cepat dan mematikan.
Berbeda dengan tentara infanteri biasa yang bergerak lamban dengan seragam berat dan barisan kaku, Marsose didesain sebagai gerilyawan tandingan, dipersenjatai dengan senjata tajam (klewang) untuk pertempuran jarak dekat. Mereka mampu mengejar pejuang Aceh hingga ke pelosok hutan dan puncak gunung.
Menariknya, sebagian besar anggota Marsose bukanlah orang Eropa, melainkan serdadu pribumi pilihan (seperti dari Ambon, Jawa, dan Minahasa) yang dipimpin oleh perwira Belanda. Mereka dianggap lebih tangguh menghadapi iklim tropis.
Puncak dari efektivitas Marsose terjadi di bawah komando J.B. van Heutsz. Dengan moto “menyerang untuk mengamankan,” Marsose mulai melakukan penetrasi ke wilayah-wilayah pedalaman yang sebelumnya tak tersentuh, seperti Gayo dan Alas.
Strategi Marsose brutal dan sistematis. Mereka tidak lagi menunggu diserang, melainkan melakukan pengejaran tanpa henti (de permanente achtervolging). Hal ini membuat para pemimpin perlawanan seperti Cut Nyak Dhien, Panglima Polim, dan Teuku Umar kehilangan ruang gerak. Logistik mereka diputus, dan perlindungan dari desa-desa dihancurkan melalui teror serta tekanan militer yang masif.
Kehancuran perlawanan Aceh secara terstruktur mulai terlihat pada awal 1900-an. Pasukan Marsose melakukan ekspedisi ke Gayo dan Alas pada tahun 1904 di bawah pimpinan Gotfried Coenraad Ernst van Daalen. Dalam ekspedisi ini, benteng-benteng pertahanan rakyat Aceh dihancurkan dengan korban jiwa yang sangat besar.
Gugurnya Teuku Umar pada 1899 dan penangkapan Cut Nyak Dhien pada 1905 menjadi simbol melemahnya pusat komando gerilya. Para pejuang yang tersisa terpaksa bergerak dalam kelompok-kelompok kecil yang terisolasi, tanpa koordinasi pusat, hingga akhirnya satu per satu menyerah atau gugur dalam pertempuran yang tidak seimbang.
Namun demikian meskipun secara resmi perang dinyatakan berakhir, api perlawanan tetap membara hingga kedatangan Jepang. Menjadi bukti betapa gigihnya rakyat Aceh dalam mempertahankan kedaulatannya hingga tetes darah terakhir, memaksa Kerajaan Belanda untuk mengerahkan semua kekuatan yang mereka miliki.