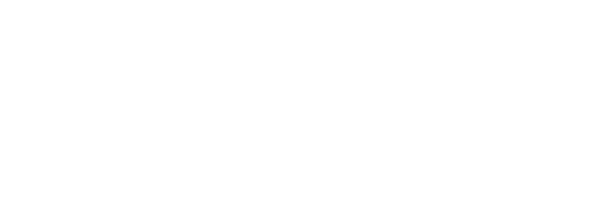Prosa Sastra karya Taufan Hunneman
Kabar5News – Si Anjing Kurap punya hidup yang relatif lumayan. Ia memiliki istri yang cantik, dengan tubuh yang “uhuyyy” bak gitar Spanyol, selalu dimandikan minyak angin agar suaranya—konon katanya—makin njreng, njring, njroooong.
Nama “Anjing Kurap” ia berikan sendiri. Katanya, sekali menggonggong, sesekali pula ia menggaruk—entah pantat, entah kepala.
Ia punya mobil lumayan, pakaian… ehmmm, lumayan, jam tangan… ehmnnn, lumayan juga. Tapi tetap saja, dia si Anjing Kurap.
Ia lahir saat kaum anjing berkumpul membicarakan tulang, daging, dan sedikit berbasa-basi ala kompeni. Tiba-tiba angin kencang mengganggu sang bayi yang masih enggan keluar dari rahim. Bunyi petir mengagetkannya: “Oweee, oweee, oweee!”—lahirlah si Anjing Kurap.
Itulah versi datar tanpa bumbu politik. Namun, versi keluarganya—kaum anjing yang kebarat-baratan—mengklaim bahwa namanya diambil dari anak seorang pemimpin besar yang tumbang oleh KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia).
“Huaahahahahaha KAMI! Huahahahaha KAMI! Blasss… jatuh… dwaaarrr!”
Si Anjing Kurap Pada Awalnya
Kisah si Anjing Kurap dimulai dari satu perjalanan yang tak pernah ia duga:
Jakarta – Surabaya – Lamongan – Jember.
Ia berjumpa anak muda dan sang kakak pembina, diberi sepucuk surat serta alamat menuju Pulau Dewata—lambang kebebasan, spiritualitas dan manusia baru.
Dalam kisahnya, ia kembali dari Bali – Banyuwangi – Solo – Yogya – Jakarta. Dalam perjalanan merenung…
Ia coba memahami satu tanda tanya besar yang tak kunjung terjawab: Kenapa ada orang miskin?
“Aku lihat… aku lihat perempuan muda, demi 50 perak, payudaranya diremas. Demi 100 perak, tubuhnya dicicipi…” gumamnya.
Ia terpukul, jatuh, dan menulis satu bait sajak:
Hari ini aku memutuskan
Keluar dari kenyamananku
Bangun dari tidurku
Aku akan mencari dan mencari
Kenapa semua itu bisa terjadi
Pos datang membawa sepucuk surat dari negeri tempat keluarga besarnya pergi. Negeri yang dikutukinya. Negeri di mana susu, keju, dan ketelanjangan adalah hal biasa.
Surat dari pamannya membakar amarahnya. Isinya tentang kata-kata filsuf, sedikit menghasut agar ia segera melawan semua sumber ketidakadilan.
Ia membaca sekali lagi dan memahami satu kalimat:
“Korupsi tidak akan pernah membuat bangsamu sejahtera.”
Kereta adalah kenangan
Kereta api menghantarkanku ke tempat kerja.
Lebih terhormat, mengumpulkan pundi-pundi uang untuk pendidikan anakku.
Lebih bahagia, menjadi seorang radikal yang berjuang untuk keluarga.
Bagiku, dahulu antara kekonyolan, kedegilan, sekaligus eksperimen hidup muda.
Sosialisme tidak lagi menarikku ke jalan revolusi.
Enough!
Bagiku, sosialisme menghadirkan keadilan bersikap.
Namun acapkali kutemui: hebat mengkritik negara, tapi gagal mengelola karakter, keluarga, apalagi jika sudah manipulatif.
Kini, aku menikmati perjalanan kereta api.
Kereta menjadi bersih, nyaman, tepat waktu.
Tidak lagi ada aksi lempar kaca.
Semua rapi.
Kereta bagiku adalah kenangan atas cinta dan pelarian dari kota ke kota sebagai mahasiswa kiri.
Stasiun adalah tempat aku bersandar di bahumu, menyusun perjalanan tanpa jejak.
Kereta api, perjalanan jauh, beromantisme, mengingatkanku pada semua tentang kemudaan, kegilaan, dan keberanian.
Tentang Seorang Perempuan
Untuk mengenang engkau—perempuan yang hobinya tak pernah pakai BH.
Sekalipun payudaramu seperti pentil jambu air depan rumahku saat di asrama, aku tetap suka padamu.
Tak pernah aku isap atau remas payudaramu yang sekali kulihat seperti kue nastar.
Aku menghormatimu, Pere.
Pere adalah mahasiswi dari kalangan teknokrat. Dalam istilah Jawa, disebut kaum priyayi modern—kolot, banyak aturan ini-itu, boleh dan tidak boleh, yang pasti semua dilanggar oleh Pere.
Mbah Kangkung, dengan gelar panjang sebagai penjaga nilai sekaligus gladiator, siap mengeksekusi jika ada nilai yang salah.
Pere suka Madilog, cinta Tan Malaka. Entah kenapa aku cemburu pada Tan Malaka. Bagiku, ia kurang radikal, kurang greget, bukan revisionis linear seperti Lenin. Tapi intinya, aku hanya cemburu.
Terlebih, fotoku kecil di dompetnya, sedangkan foto Tan besar ditaruhnya.
Ia ingin hidup di tahun 1920-an, saat Tan di Belanda, lalu kembali ke tanah Jawa. Imajinasi liar Pere membuatku semakin tak tertarik pada Tan Malaka.
Sedangkan aku bukan dari kalangan priyayi.
Ibuku anak pedagang, tersusun dari kalangan ulama, tentara, dan polisi.
Ayahku berdarah VOC, pedagang, dan juga seorang perempuan lihai asal Kediri yang jago memanah hati lelaki tiga tahun lebih muda.
Buyutku dari Kediri, tapi sejatinya masih terpaut dengan keturunan Tionghoa.
Pere wafat di usia muda.
Sakit.
Keluarganya berduka.
Airmataku berlinang.
Teringat jelas perjalanan kereta terakhir bersamanya di kelas ekonomi, di lantai teras gerbong kereta api.
Malam itu, tanganmu enggan melepasku.
Manja.
Sekali payudaramu, bagai pentil jambu air itu, menempel ke tulang-tulangku.
Antara birahi, cinta, dan sayang.
Semua tidur terlelap di gerbong penuh manusia.
Aku kecup bibirmu, kuraba payudaramu, kututupi dengan jaket pilot belel pemberian kakakku agar aku kuliah naik motor—motor yang tak pernah aku naiki.
Malam itu, kenangan pertama, terindah yang pernah aku alami sebagai mahasiswa semester dua.
Kini aku tidak lagi terlalu dalam mengingat Pere.
Yang kuingat: istriku.
Bohay alias si aduhai yang tak bisa bergoyang.
Senyumnya tipis-tipis, tapi kalau tertawa… terbahak-bahak.
Aku tetap sama.
Dengan suara lantang, kugetarkan podium pidato.
Mengelegar, tepat di jantung setiap orang.
Membuat goncangan, membuat orang berhenti dan berpikir:
Jika saudara tidak korupsi, maka itulah keadilan.
Sebab, itu memberi kesempatan generasi ke generasi untuk menjadi makmur.
Jangan tinggalkan warisan utang dan keruwetan pada generasi yang akan datang.
Siapkan jalan kemakmuran.
Pidatonya bagai politisi, tapi aku enggan berpolitik.
Aku si Anjing Kurap.
Lahir di Jakarta.
Besar di Jakarta.
Menjadi anak Jakarta.
Dan tak ingin merantau.
Namun aku suka melancong ke Bali.
Di sana, aku bisa melihat Nusantara.