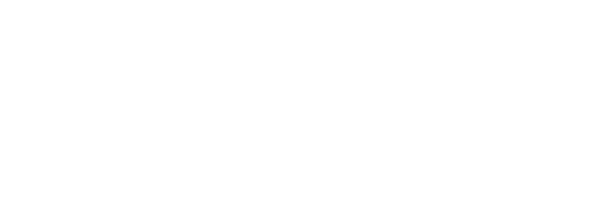Kabar5News – Konflik agraria di Indonesia bukanlah persoalan baru dan sudah terjadi selama ratusan tahun. Hal itu disampaikan Dosen Hukum Universitas Sains Indonesia, Syaiful Bahari, dalam Focus Group Discussion yang digelar Kabar5News di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Syaiful mengatakan, sejak masa kolonial, kebijakan pertanahan telah membentuk struktur ketimpangan penguasaan lahan yang dampaknya masih terasa hingga sekarang.
Doktrin domein verklaring dan kebijakan agraria kolonial menempatkan tanah adat sebagai milik negara, sehingga membuka ruang konsentrasi lahan pada korporasi besar.
“Sejarah pertanahan kita sejak awal dibangun di atas logika penguasaan, bukan perlindungan. Di sinilah akar konflik itu bermula,” ujar Syaiful.
Warisan tersebut kemudian berusaha diperbaiki melalui Pasal 33 UUD 1946 yang menyatakan bahwa bumi dan air dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, serta melalui Undang-Undang Pokok Agraria yang dirancang sebagai instrumen keadilan sosial.
Namun dalam praktiknya, lanjut Syaiful, implementasi kebijakan agraria sering kali inkonsisten.
“Hak menguasai negara seharusnya dimaknai sebagai fungsi pengayoman dan pengaturan untuk kepentingan publik, bukan legitimasi untuk menyerahkan lahan kepada kepentingan tertentu,” ungkap Syaiful yang juga pemerhati kebijakan agraria.
Menurutnya, perbedaan tafsir, lemahnya pengawasan, serta dominasi kepentingan ekonomi membuat konflik agraria terus berulang.
Konflik Agraria Saat Ini: Alih Fungsi dan Ketimpangan Akses
Dalam konteks kekinian, konflik agraria seringkali dipicu oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, perumahan, dan perkebunan skala besar.
Lahan produktif yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan petani beralih menjadi objek investasi.
“Petani kecil sering kali berada pada posisi paling lemah ketika berhadapan dengan korporasi yang memiliki akses modal dan perizinan,” jelas Syaiful.
Sengketa hak ulayat antara masyarakat adat dengan negara maupun investor juga terus terjadi, terutama dalam ekspansi perkebunan sawit dan proyek strategis.
Selain itu, ketimpangan akses terhadap pembiayaan dan pengelolaan sumber daya air memperburuk situasi.
“Konflik agraria bukan hanya soal kepemilikan tanah, tetapi juga soal akses terhadap sumber produksi,” tambahnya.
Potensi Konflik ke Depan: Tekanan Pembangunan dan Energi
Ke depan, potensi konflik diperkirakan semakin kompleks seiring tekanan pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan energi terbarukan.
Konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan non-pertanian dikhawatirkan terus meningkat.
“Jika perlindungan lahan pertanian tidak diperkuat, kita bukan hanya menghadapi konflik sosial, tetapi juga ancaman terhadap ketahanan pangan nasional,” ujar Syaiful
Kebijakan berbasis ekspansi komoditas dinilai perlu diimbangi dengan strategi intensifikasi dan peremajaan lahan agar tidak memperluas pembukaan wilayah baru.
Mengapa Perlu Solusi Struktural?
Konflik agraria pada akhirnya menyangkut keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan. Dalam kesempatan yang sama, Dosen UCIC Cirebon, Taufan Hunneman mengatakan, tanpa reforma agraria yang konsisten, yang mencakup perlindungan lahan, penguatan hak masyarakat adat, serta pemerataan akses terhadap sumber daya, ketegangan antara negara, korporasi, dan petani akan terus terjadi.
“Penyelesaian konflik agraria harus ditempatkan sebagai agenda strategis nasional, bukan sekadar persoalan administratif,” tegas Taufan.
Pada akhirnya, lanjut Taufan, keberhasilan menata ulang kebijakan agraria akan menentukan arah ketahanan pangan dan stabilitas sosial Indonesia di masa depan.